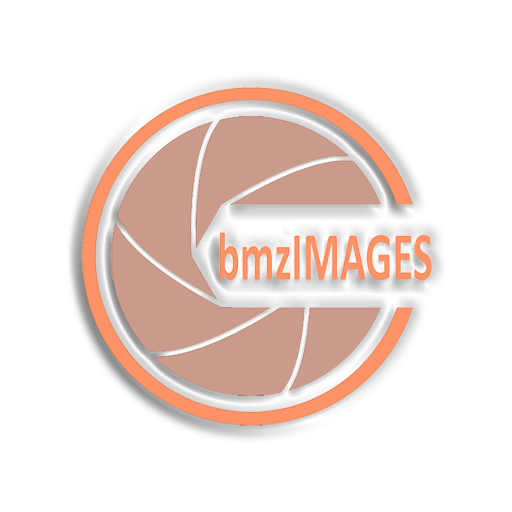WAKTU sudah menunjukkan pukul 07.00 Wita, tapi Indrawati Sambow (35) belum juga muncul. Rizal (32) dan Arjon (29) sesamanya guru bantu sudah tak sabar lagi. Keduanya mulai membayangkan perjalanan yang bakal melelahkan, karena terik matahari pasti akan membakar tubuhnya saat menyusuri jalan setapak menuju puncak gunung Topesino.
Di puncak gunung itu, sedikitnya terdapat 48 KK bermukim. Mereka nyaris terisolasi dari dunia luar karena tak ada satu pun sarana transportasi yang bisa digunakan untuk mencapainya selain berjalan kaki. Kemiringannya yang rata-rata lebih dari 45 derajat membuat siapapun selalu berpikir untuk melakukan perjalanan dari dan menuju dusun bernama Topesino yang masih berada di wilayah Desa Mantikole, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
Tepat pukul 07.30, Indrawati akhirnya muncul juga. Mereka bertiga menyusuri jalan setapak berliku yang terus mendaki. Sesekali ketiganya terlihat berhenti untuk beristirahat, menyeka keringat dan meneguk air putih yang dibawa dari rumah masing-masing. Sesekali pula terdengar senandung merdu dari bibir Indrawati, mungkin saja seperti itulah dia menghibur dirinya melewati panggilan tugas.
Indrawati adalah guru bantu, sedangkan Rizal dan Arjon adalah tenaga honorer yang tamatan SMU. Sejak dua tahun terakhir, ketiganya mendedikasikan diri untuk menjadi tenaga pengajar kelas jauh SD Inpres Mantikole di Dusun Tompesino yang letaknya di puncak gunung tersebut.
Sebagai tenaga lepas, mereka rata-rata dibayar Rp.300.000 per triwulan untuk pengabdiannya itu. Ketiganya menetap di kaki gunung Topesino yang jaraknya tidak lebih dari lima kilometer dari puncak gunung itu. Jaraknya memang tidak seberapa, tapi setiap kali menuju sekolah mereka membutuhkan waktu tercepat sampai tiga jam karena medan yang terus mendaki dan berliku. “Pernah ada yang datang ke sekolah kami, mereka butuh waktu sampai 5 jam,” ujar Indrawati bangga, seolah menyatakan dirinya jauh lebih cepat dari orang yang tidak terbiasa melalui medan tersebut.
Tepat pukul 10.30, ketiganya sampai di sebuah pondok dengan sebuah bale-bale terbuat dari papan kasar. Pondok itu beratap rumput-rumput kering yang dibuat sedemikian rupa agar tidak tembus hujan. Berlantai tanah dengan bekas-bekas sisa pembakaran dan sebuah lubang agak besar di tengahnya. Di depan lubang itu tergantung sebuah papan tulis putih. “Inilah sekolah kami,” kata Indrawati.
Tampakan sekolah itu sudah berubah katanya, sebelumnya punya dinding dari daun-daun yang dianyam sedemikian rupa, makanya pula sebelumnya lebih popular disebut ‘Sekolah Daun’. “Tapi dinding itu sudah dilepas karena gelap,” imbuhnya.
Sekolah tidak langsung digelar, Indra bersama rekannya harus mendatangi rumah-rumah para muridnya untuk mengajaknya ke sekolah. Hanya sebagian diantara 20 orang muridnya yang memiliki seragam putih-merah, itupun bisa diadakan setelah warga kaki gunung menyumbang anak-anak tersebut dengan pakaian bekas.
Kumandang lagu Indonesia Raya terdengar dari gubuk yang disebut sebagai sekolah itu menandai dimulakannya kegiatan belajar. Indrawati memandu anak-anak bernyanyi penuh semangat. “Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin,” kata Indra di depan kelas. Secara bergantian, Rizal dan Arjon juga membimbing anak-anak itu. Sebagian diantaranya sudah mahir membaca, namun sebagian lagi baru bisa mengenal huruf.
Sudah dua tahun terakhir ini ketiganya mengabdi untuk sekolah kelas jauh tersebut. Letih memang, tapi itulah pengabdian yang bisa dilakukannya untuk masa depan anak-anak bangsa, meski harus digaji Rp.100.000 per bulan. ***
Naskah dan foto: Basri Marzuki