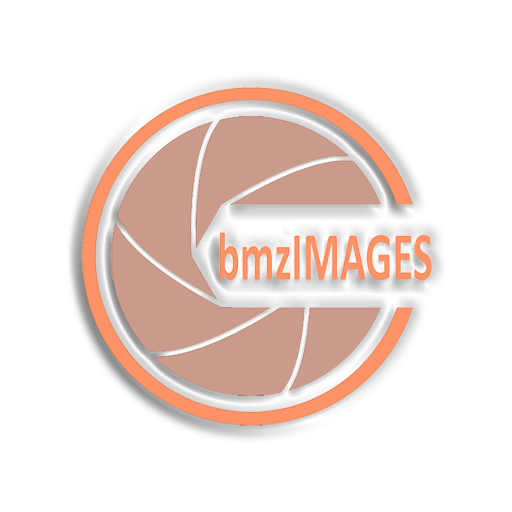Those who Bet on the Front Guard COVID-19
A medical officer prepares a logistical isolation room for patients under surveillance…
Merajut Asa di Pulau Kabalutan
PUKUL 05.58 Wita, mentarimembersitkan sinarnya di ufuk timur. Seketika, riuh menyeruak di…
Secercah Optimisme dari Mantan Tapol
BABAK kesuraman hidup itu dimulai ketika pimpinan negara menumpas gerombolan Partai Komunis…
Melepas Getirnya Hidup di Rumah Jagal Sapi
PUKUL 02.00 Wita, Aco – demikian ia disapa, sudah siap dengan pisaunya…
La Haku: Hidupku Ada di Kepalamu”
UNTUK pria seumurnya, ia terbilang masih cukup fit. Tuas kakinya masih kokoh menopang…
Bertaruh Untuk Kelangsungan Hidup
BIBIR Pak Ahmad sumringah ketika kami tiba di dermaga Pulau Pasoso. Pulau…
Setiawati, Harapan Tak Berujung
SETIAWATI, demikianlah nama gadis kelahiran 19 tahun lalu ini. Matanya menatap hampa ke…
Masih Ada Harapan
WAKTU masih menunjukkan pukul 07.00, tapi Ihsan (7) sudah muncul di depan…
Senin Kelabu di Jalan Monginsidi
HARI itu Senin, 2006, Pendeta Irianto Kongkoli keluar dari rumahnya yang terletak…
Poso Riot Convict
Three Poso riot defendants, Fabianus Tibo (left), Marunis Ruwu (center), and Dominggus…